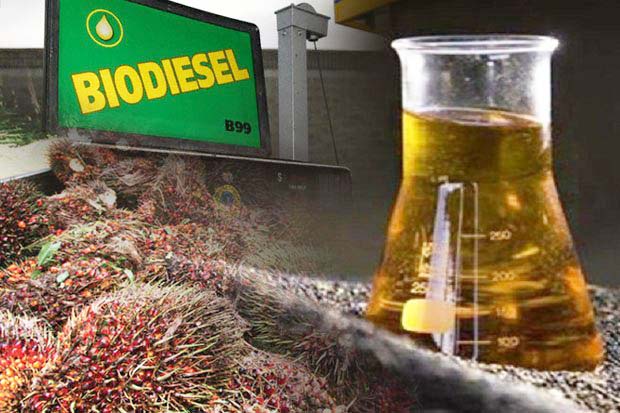Potensi Cangkang Telur Ayam (Gallus gallus) menjadi Sumber Energi Listrik dengan Proses Kalsinasi
Ide ini secara spontan terlintas dipikiran ketika melihat tante saya yang sedang membuat kue. Semua bahan yang ada diatas meja dicampurkan dan siap diubah menjadi adonan kue yang kemudian akan di panggang di dalam oven. Hingga akhirnya mata saya tertuju pada tumpukan cangkang telur yang berada di bawah meja.
Selama ini saya menyadari bahwa cangkang telur umumnya hanya di daur ulang menjadi sebuah kerajinan tangan, katakanlah: guci, lukisan, dan miniatur-miniatur mini yang sangat kecil dan kompleks yang dibuat dengan indah menggunakan tangan. Namun jarang sekali yang memanfaatkan limbah cangkang telur ini dalam bidang pemanfaatan energi, padahal cangkang telur ini tak jarang kita temukan dalam limbah rumah tangga, terlebih lagi limbah ini sering ditemukan di bagian sampah dapur anak kost, bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa santapan anak kost pada dasarnya tak akan pernah jauh dari hidangan indomie dan telur.
Pemanfaatan cangkang telur sebagai alternatif listrik merupakan solusi yang tepat guna menciptakan sebuah inovasi energi pada masa kini. Hal ini sesuai dengan UU Lingkungan hidup No. 81 tahun 2012 mengenai pengelolaan sampah atau limbah rumah tangga dan sampah sejenis sampah atau limbah rumah tangga. Dari data Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, jumlah produksi telur pada tahun 2018 mencapai angka 73.078 ton/tahun dan angka ini akan selalu bertambah dari tahun ke tahunnya. Menurut data World Intellectual Property Organization (2009), di Amerika Serikat, ada sekitar 190.000 ton kulit telur yang terbuang, yang dari jumlah ini, sekitar 120.000 ton dihasilkan dari industri pengolahan makanan dan sekitar 70.000 ton dihasilkan dari penetasan telur. Sementara itu, di Indonesia produksi kulit telur akan terus berlimpah selama telur diproduksi di bidang peternakan serta digunakan di restoran, pabrik roti dan mie sebagai bahan baku pembuatan makanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limbah dari cangkang telur ini banyak dibuang secara percuma apabila tidak bisa dimanfaatkan secara bijak. Jika teknologi ini dapat dikembangkan, maka akan meningkatkan nilai guna dari limbah cangkang telur sehingga tidak hanya sekedar menjadi limbah rumah tangga, tetapi juga dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.
Cangkang telur yang sudah kita anggap sebagai limbah rumahan ini ternyata mengandung listrik apabila dikaji dengan studi ilmiah. Kulit telur kering mengandung sekitar 95% kalsium karbonat dengan berat 5,5 gram (Butcher dan Miles, 1990). Berdasarkan hasil penelitian, serbuk kulit telur ayam mengandung kalsium sebesar 401 ± 7,2 gram atau sekitar 39% kalsium, dalam bentuk kalsium karbonat (Schaafsma, 2000). Sementara itu, Hunton (2005) melaporkan bahwa kulit telur terdiri atas 97% kalsium karbonat. Selain itu, rata-rata dari kulit telur mengandung 3% fosfor dan 3% terdiri atas magnesium, natrium, kalium, seng, mangan, besi, dan tembaga (Butcher dan Miles, 1990).
Proses yang digunakan pada percobaan ini adalah proses kalsinasi. Kata kalsinasi berasal dari bahasa latin yaitu calcinare yang artinya membakar kapur. Proses kalsinasi yang paling umum dilakukan adalah pengaplikasiaanya untuk dekomposisi kalsium karbonat (CaCO3) menjadi kalsium oksida (CaO) dan gas karbondioksida (CO2). Produk dari kalsinasi biasanya disebut “kalsin”, yaitu mineral yang telah mengalami proses pemanasan (Andra, 2013). Berdasarkan penelitian Andra (2013), proses kalsinasi dilakukan dalam sebuah tungku atau reaktor yang disebut dengan kiln atau calciners dengan beragam desain seperti tungku poros, rotary kiln, tungku perapian ganda, dan reaktor fluidized bed. Normalnya proses kalsinasi dilakukan dibawah temperature leleh (melting point) dari bahan produk. Untuk batu kapur, proses kalsinasi umumnya dilakukan pada temperature antara 900oC – 1000oC. Menurut penelitian Nurlaela dkk (2014), Proses kalsinasi mengakibatkan massa cangkang telur berkurang. Dari cangkang telur ayam diperoleh 65,67% (b/b) serbuk hasil kalsinasi. Menurut penelitian Edy dan Rio (2013) yang berjudul pembuatan gypsum dari limbah cangkang telur, sampel cangkang telur setelah dikalsinasi beratnya berkurang dari 1 Kg menjadi 657 gram, ini disebabkan terjadi dekomposisi dan pelepasan senyawa CO2 dari senyawa CaCO3 yang terkandung didalam cangkang telur menjadi CaO yang persamaan reaksinya adalah sebagai berikut :
CaCO3(S) → CaO(s) + CO2(g)
Tahap pertama dari proses pengolahan cangkang telur menjadi energi listrik adalah bahan baku yang berupa cangkang telur dibersihkan dan dikeringkan, kemudian dihaluskan dengan mortar porselen. Setelah halus, kemudian dilakukan proses kalsinasi, atau pembakaran sampel cangkang telur. Cangkang telur dikalsinasi dengan furnace pada suhu 900oC selama 2 jam. Cangkang yang telah melewati proses kalsinasi ini kemudian akan direaksikan dengan H2SO4 (asam sulfat) dan H2O (air) sehingga terjadi reaksi eksoterm. Hasil dari proses ini kemudian dipanaskan kembali dan dilarutkan dengan akuades. Dan dari proses ini kemudian akan dihasilkan energi panas yang diperoleh dan dirangkai dengan termoelektrik untuk diukur analisa besar daya yang dihasilkan kemudian baru bisa dikonversikan menjadi energi listrik.

Statement terakhir dari saya, sumber energi yang berasal dari olahan limbah organik masih harus dieksplorasi dan dikaji lebih lanjut secara efektif, sehingga kebutuhan energi umat manusia pada masa kini dapat terpenuhi, terlebih apabila limbah organik tersebut bisa diolah menjadi sumber atau cadangan energi di masa mendatang. Dengan menggunakan cangkang kulit telur yang ‘hanya’ berpotensi menjadi limbah rumahan saja, dapat diubah menjadi limbah yang bermakna dan memiliki nilai ekonomis apabila ditangani dengan cara yang tepat.
Kata Kunci: Cangkang telur, Kalsinasi, Reaksi eksoterm, Energi alternatif.